DASAR-DASAR TEORI WUJUD IBNU ‘ARABI
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang Masalah
Di dalam Islam, sufisme memberi makna isoteris
yang melandasi formalisme. Mengkaji tasawuf berarti mempelajari dimensi-dimensi
isoterik dari sebuah bangunan kepercayaan, sehingga sebuah agama (Islam) dapat
dipandang secara utuh dan universal, bukan sekedar dogma-dogma yang mengukung
tanpa makna. Apabila Islam dipisahkan dari aspek ini, maka hanya menjadi
kerangka formal. Ibaratnya apabila kerangka tersebut tidak dibalut dengan
daging dan kemudian dihidupkan sesungguhnya keindahan Islam tidak akan pernah
ditemukan.
Jika dulu Aristoteles mengklasifikasikan
hal-hal dalam 10 kategori yaitu substansi, ruang, waktu, kualitas, kuantitas
dan lain-lain kini manusia modern mereduksi dirinya menjadi satu kategori saja
yaitu kuantitas. Nilai-nilai yang dianut manusia dalam menentukan
keberhasilannya diukur dari hal-hal yang empirik, material dan bersifat
biologis. Lalu bagaimana peran agama dalam menghadapi krisis spiritual dunia
modern? Kenyataannya adalah meskipun agama tetap dipegang akan tetapi hanya
menjadi kerangka formalitas yang tidak mempunyai makna dan kekuatan untuk
mengatur roda kehidupan.
Adalah penting untuk menyadari bahwa
spiritualitas tidak hanya sekedar bagian dari relitas manusia, tetapi
spiritualitas adalah keseluruhan makna manusia. Keseluruhan integral ini adalah
batu fondasi dari kesadaran diri, dan mencakup semua aspek khusus (manusia). Ia
menjadi terlihat di dalam apa-apa yang kita ketahui dan pahami, di dalam bagaimana
kita bertindak, berpikir, dan merasakan. Singkatnya kita adalah makhluk
spiritual dan keseluruhan dari apa yang disebut dengan dunia material
diruhanikan. Kita harus hati-hati terhadap pemikiran yang menganggap
spiritualitas hanya berhubungan dengan salah satu fakultas dalam diri kita,
atau sebagai sesuatu yang sepenuhnya berada di luar dunia ini, yang tidak ada
kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati agar tidak
terjatuh ke dalam perangkap intelektual yang terlalu mudah memisahkan akal dari
intuisi, kepala dari hati. Ini jauh dari realitas yang dijelaskan oleh Ibnu
‘Arabi. Bagi dia, setiap realitas dunia, atau setiap aspek dari dunia, hanya
dapat dipahami dengan tepat melalui asal-usul spiritualnya. Ia menghubungkan
setiap realitas keduniawian dengan prinsip ilahiahnya, dan karena itu
menempatkan segala sesuatu di tempat yang sebenarnya.[1]
Dengan demikian pengkajian terhadap nilai-nilai
spiritual sekaligus filosofis diharapkan mampu menghidupkan kembali eksistensi kemanusiaan
kita yang nyaris terlupakan. Sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan rohani
di tengah peradaban moderen yang gersang. Selain itu dimaksudkan untuk
melestarikan pemikiran-pemikiran paratokoh islam dengan mencari sisi-sisi
positif yang mungkin untuk dipertimbangkan dalam menghadapi zaman global.
Di dunia tasawuf dikenal banyak memiliki konsep
tentang Al-Wahdah, seperti Al-Wahdat Al-Ummah, Al-Wahdat Al-Wujud, Al-Wahdat
Al-Adyan, dan sebagainya. Ibnu Arabi sangat sering dikenali sebagai penerus pertama
doktrin wahdat al-wujud “Kesatuan Tuhan” atau “Kesatuan Eksistensi”.
Sesungguhnya karya yang khusus menampilkan sudut pandangnya kebanyakan bukan
isi dari tuilisan-tulisanya, namun karena perhatian para pengikutnya dan arah
pemikiran Islam yang berkembang setelah dirinya.
Istilah wujud secara tipikal diterjemahkan dalam
bahasa inggris dengan Being atau Existence, dan ini lazim seperti keadilan yang
sering digunakan dalam Filsafat Islam maupun Kalam (Teologi Dogmatis). Namun,
pengertian dasar dari istilah tersebut adalah “menemukan” (finding) atau
“ditemukan” (to be Found), kata wujud merupakan bentuk masdar dari kata wajada
(menemukan) atau wujida (ditemukan) yang berasal dari kata wajada.
B.Rumusan
Masalah
Dari latar belakang di atas penulis merumuskan beberapa
rumusan masalah :
1.
Biografi Ibn ‘Arabi
2.
Makna Wahdah al-Wujud
3.
Dasar-dasar
teori Ibnu ‘Arabi tentang Wahdah al-Wujud
BAB II
PEMBAHASAN
DASAR-DASAR TEORI WUJUD IBNU ‘ARABI
A.
Biografi Ibnu ‘Arabi
Nama lengkap
Ibnu ‘Arabi adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah
al-Hatimi. Ia keturunan dari Abdulah bin Hatim saudara Adiy bin Hatim dari
kabilah Thai. Kuniahnya adalah Abu Bakar dan laqab (julukannya) adalah
Muhyiddin. Ia juga populer dengan sebutan Al-Hatimi dan dengan sebutan Ibnu
Arabi (tanpa “al”) untuk membedakannya dengan Qadhi Abu Bakar ibn al-Arabi.
Mendapat gelar Syaikh al Akbar
(Doktor Maximus). Lalu banyak penulis yang menggabungkan dua gelar itu
menjadi : Syaikh al Akbar Muhyidin Ibnu Arabi. Ibnu Arabi lahir pada hari Senin tanggal 17
Ramadhan 560 H bertepatan dengan 28 Juli 1165 M di Murcia, Spanyol bagian
tenggara, Andalusia[2].
Ibnu ‘Arabi
berasal dari keluarga kaya, terpandang dan keluarga yang penuh dengan
ketaqwaan. Ibnu ‘Arabi memiliki dua
paman yang sangat zuhud, yaitu Yahya, seorang paman yang rela meninggalkan
jabatannya sebagai pejabat kemudian berusaha mencari kayu ke hutan dan
menjualnya untuk keperluan sehari-hari. Dan Abu Muslim al-Khaulani seorang yang
selalu beribadah di malam hari.[3]Ayahnya
-Ali bin Muhammad- termasuk salah seorang ahli fiqh dan hadits, juga seorang
sufi yang zuhud dan bertaqwaAyahnya adalah orang shalih yang senantiasa tekun
membaca Al-Qur’an dan memiliki beberapa karamah, di antara karamahnya adalah
bahwa ia tahu hari meninggalnya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Arabi
dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makiyah.
Semasa
remajanya, seperti remaja-remaja lain, ia juga punya waktu untuk
bersenang-senang selain dari waktu belajarnya.[4] Pada
satu masa ketika ia lagi bersenang-senang di Sevilla, dia telah mendengar suara
yang memanggilnya beliau, “Hai Muhamad, bukan untuk ini kamu diciptakan.” Ia
menjadi gelisah dan penasaran dengan pengalaman ini. Dalam kegelisahan itu, ia
melarikan diri dan menyendiri untuk beberapa hari di sebuah tempat pekuburan.
Di situlah Ibn ‘Arabi mengalami tiga musyahadah yang mempunyai pengaruh
besar dalam perkembangan spiritual masa depannya. Dia telah bertemu Nabi Isa,
Musa, dan Muhammad—yang telah memberi instruksi spiritual untuknya.[5]
Pada umur
delapan tahun, Ibn ‘Arabi meninggalkan kota kelahirannya dan berangkat ke
Lisbon, untuk menerima pendidikan agama Islam pertamanya, yaitu membaca
al-Qur’an dan mempelajari hukum-hukum Islam dari Syekh Abu Bakar bin Khalaf,
kemudian ia pindah ke Seville yang saat itu merupakan pusat sufi Spanyol dan
menetap di sana selama tiga puluh tahun untuk mempelajari hukum, hadits,
teologi Islam, serta banyak belajar dari ulama-ulama dalam mempelajari tasawuf.
Ia belajar tasawuf kepada sejumlah sufi terkenal seperti Abu Madyan al-Gauts
at-Talimsari, dan melanglang buana ke berbagai negeri seperti Yaman, Syiria,
Irak, Mesir, dan akhirnya pada tahun 620 H, ia menetap di Hijaz hingga akhir
hayatnya.
Ketika
ia berusia 30 tahun ia mulai berkelana ke berbagai kawasan Andalusia dan
kawasan islam bagian barat. Diantara guru-gurunya adalah Abu Madyan al-Ghoust
al-Talimsari seorang pendiri aliran tasauf dan Yasmin musaniyah. Keduanya banyak
dipengaruhi ajaran-ajaan Ibn ‘Arabi. Dikabarkan juga bahwa dia pernah ketemu
dengan ibn Rusyd. Filosof murni dan tabib istana dynasty barbar dari Alomohad di
kordova.[6] Dan
pertemuan Ibn ‘Arabi dengan Ibn Rusyd termasuk pertemuan yang luar biasa bagi
ibn Arabi. Setelah pertemuannya dengan Ibnu
Rusyd dan mengalami pencerahan spiritual, pada tahun 580 H (1184), Ibn’ ‘Arabi
mengundurkan diri dari ketentaraan dan segala urusan duniawi yang dimilikinya. Ia juga telah
dikabarkan mengunjungi Al-mariyyah yang menjadi pusat madrasah ibn Masarrah
seorang sufi falsafi yang cukup berpengaruh dan mempunyai banyak masalah di
Andalusia, di antara karya monumenalnya yaitu al-futuhat al-makkiyah yg ditulis pada tahun 1201 H. Tatkala ia
sedang menunaikan ibadah haji. Karya lainnya yaitu Turjumân al-Asyuwaq yang ditulisnya untuk mengenang
kecantikan, ketakwaan, dan kepintaran seorang gadis cantik dari keluarga
seorang sufi dari Persia.[7] tapi sebenarnya karya itu merupakan ungkapan cintanya kepada Sang
Pencipta.[8]
B.
Dasar-dasar Teori Wujud Ibnu ‘Arabi
1. Makna
Wahdah al-Wujud
Sebelum melangkah pada pembahasan mengenai
konsep waĥdatul wujūd, sebaiknya yang pertama kali kita uraikan adalah
istilah kuncinya, yakni wujūd. Banyak penulis merasa kesulitan dalam
menemukan suatu terjemah yang tepat bagi kata wujūd.[9] Kebanyakan dari mereka lebih memilih tidak
menerjemahkan istilah ini ke dalam kata yang pendek atau singkat. Mereka tetap
menggunakannya dengan terlebih dahulu diberi penjelasan panjang lebar, sebagai
konsep yang independent maupun digunakan sebagai bahasa teknis yang disesuaikan
dengan konteksnya.
Kata wujūd mempunyai pengertian obyektif
sekaligus subyektif.[10] Dalam
pengertian obyektif, kata wujūd adalah masdar dari wujida yang
artinya “ditemukan”. Dalam pengertian ini biasanya wujūd diterjemahkan
ke dalam bahasa Inggris menjadi being atau existence atau “ada”
dan di dalamnya terdapat aspek ontologis[11],sedangkan
dalam pengertian subyektif wujūd adalah masdar dari wajada yang
berarti “menemukan”. Biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi finding
dan di dalamnya terdapat aspek epistemologis[12] dalam
sistem Ibnu ‘Arabi, kedua aspek ini menyatu secara harmonis.[13] Pada
satu fihak, wujūd atau satu-satunya wujūd adalah “menemukan”
Tuhan yang dialami oleh Tuhan sendiri dan para pencari rohani. Orang-orang yang
“menemukan” Tuhan oleh Ibnu ‘Arabi disebut sebagai ahlu kasyf wal wujūd(orang-orang
yang menyingkap dan menemukan).[14]
Ketika Ibnu ‘Arabi berbicara tentang sesuatu
yang spesifik atau suatu ide yang dapat didiskusikan, dia menggunakan term
eksistensi yang artinya sesuatu itu ada dan dapat ditemukan. Dalam pengertian
ini kita dapat mengatakan bahwa Tuhan mewujud atau “Tuhan ada dan ditemukan”[15]
Seperti
hubungan antara timur dan barat, depan dan belakang, jika wujūd diartikan
sebagai “yang ada” atau eksistensi, kita akan dihadapkan pada konsekwensi
logisnya yakni ‘adam, “ketiadaan” atau non eksistensi. Hubungan wujūd dengan
‘adam dinisbatkan secara mutlak oleh Ibnu ‘Arabi sebagai hubungan antara
cahaya dan kegelapan. Wujūd adalah cahaya dan ‘adam adalah
kegelapan, karena itu wujūd atau cahaya adalah milik Tuhan sedangkan ‘adam
atau kegelapan adalah milik alam atau kosmos.[16]
Pengertian
wujūd yang senada juga telah dikemukakan oleh A E. Affifi yakni (a) wujūd
sebagai suatu konsep : ide tentang wujūdeksistensi atau wujūd bil ma’na al
masdari, (b) wujūd berarti yang mempunyai wujud, yakni yang ada atau yang hidup
atau wujūd bil ma’na maujūd.[17]
Wahdat
al-wujud adalah ungkapan yang terdiri dari dua kata yaitu wahdat dan al-wujud.
Wahdat artinya sendiri, tunggal atau kesatuan sedang al-wujud artinya ada.[18] Dengan
demikian wahdat al-wujud berarti kesatuan wujud.
Harun
nasution lebih lanjut menjelaskan paham ini dengan mengatakan bahwa paham
wahdat al-wujud nasut yang sudah ada dalam hulul diubah menjadi khalq (makhluk)
dan lahut menjadi haqq (tuhan).Aspek yang sebelah luar disebut khalq dan aspek
yang di sebelah dalam disebut haqq.[19]
Persepsi
tentang waĥdatul wujūd dapat dianalogikan dengan apa yang kita pahami
ketika ada sorot cahaya menembus sebuah prisma : sekalipun terdapat banyak
warna cahaya yang berbeda, namun kita memahaminya hanya berupa cahaya, karena
hanya cahayalah yang eksis. Ibnu ‘Arabi mengatakan bahwa wadah manifestasi
Tuhan bersifat jamak karena keanekaragaman sifat-sifat dan efek yang
ditampilkan. Namun mereka satu, karena kesatuan wujud yang menjelmakan di
dalamnya. Kesatuan muncul dalam manifestasi wujud (segala sesuatu), sementara
keragaman bersemayam dalam entitas-entitas yang tidak memiliki eksistensi
sendiri. Oleh karena itu, Tuhan dalam keesaan-Nya adalah identik dengan wujud
dari segala sesuatu, tetapi Dia juga tidak identik dengan segala sesuatu itu.[20]
2.
Dasar-dasar
Teori Wujud Ibnu ‘Arabi
Dalam
membangun doktrin waĥdatul wujūdnya, Ibnu ‘Arabi mendapat pengaruh dari
prinsip-prinsip emanasi dan hirarki Neoplatonisme. Meskipun keduanya tidak
dapat dikatakan identik –karena Ibnu ‘Arabi sangat ekletik terhadap sumber
lain– tetapi pengaruh itu diakui tetap ada.
Ada
kesamaan yang mendasar antara pemikiran Plotinus tentang The One dengan
pemikiran Ibnu ‘Arabi tentang waĥdatul wujūd. Seperti filsafat pada
umumnya, keduanya membicarakan seputar tema yang mencakup Tuhan, alam, manusia
dan bagaimana bentuk hubungan antara ketiganya. Kesamaan yang mendasar dari
keduanya adalah bahwa antara Tuhan, alam dan manusia merupakan satu kesatuan
yang utuh, hal ini terlepas dari perdebatan mengenai istilah panteisme dan
monisme. Namun yang membedakan keduanya adalah bagaimana bentuk hubungan
tersebut sehingga ketiganya disebut sebagai satu kesatuan.
Intisari dari seluruh sistem Ibnu ‘Arabi adalah satu
realitas yang mengungkapkan atau memanifestasikan dirinya dalam bentuk-bentuk
yang tidak terbatas, bukan realitas yang memunculkan atau melahirkan atau
mengemanasikan sesuatu seperti halnya dalam pemikiran Plotinus[21] dalam Waĥdatul wujūd, segala sesuatu yang
maujud adalah pantulan dari wujūd mutlak, oleh karena itu sifat
kesempurnaan dalam setiap pantulan sesuai dengan urutan-urutan kejadiannya atau
sesuai dengan jauh dekatnya jarak dari wujūd mutlak, Ibnu ‘Arabi
menamakan ini sebagai Tajalliyat. Jadi, adanya keanekaragaman termasuk
alam dan manusia, merupakan hasil dari pengejawantahan atau tajalli
Tuhan dan bukan dari proses emanasi.[22]
Meskipun
dalam hal penggunaan terminologi, Ibnu ‘Arabi sering mengikuti Plotinus[23],tetapi
doktrin emanasi Neoplatonisme diartikan oleh Ibnu ‘Arabi dengan caranya sendiri
yang sama sekali lain dari yang dimaksudkan oleh Plotinus. Pada doktrin emanasi
Neoplatonik, pergerakan terjadi secara progresif menurut garis lurus atas ke
bawah. Pergerakan itu merupakan rangkaian emanasi-emanasi yang tiap anggota
secara misterius menciptakan anggota baru. Hasil dari ciptaan itu bersifat
lebih rendah dan mencerminkan kesempuranaan dari yang lebih tinggi[24]. Berbeda
dengan pandangan Ibnu ‘Arabi yang menganggap adanya intelek pertama, jiwa
universal dan tubuh universal sebagai hasil dari cara yang berbeda-beda dalam
pengungkapan diri dari yang satu, bukan berada dalam satu garis lurus yang
hirarkis. Tajalli adalah manifestasi diri yang abadi tanpa akhir, kadang
sebagai esensi dan kadang sebagai suatu bentuk atau form.[25]
Bedanya
hirarki martabat wujud ini dari tiga hipotesis Plotinus terletak pada alam
empiris. Jika dalam sistem Ibnu ‘Arabi alam empiris atau materi merupakan
anggota penuh dari hirarki tajalli, sedangkan menurut Plotinus alam empiris
atau materi tidak termasuk tritunggalnya, karena baginya materi merupakan
prinsip kegelapan dan sumber kejahatan.[26]
Ada
hal lain yang membedakan antara emanasi Plotinus dengan tajalliyat Ibnu ‘Arabi.
Dalam emanasi Plotinus, lahirnya hipostatis kedua dan ketiga sampai akhirnya
melahirkan materi adalah suatu keniscayaan yang begitu saja terjadi, tanpa
terencana dan kehendak.[27] Sedangkan
menurut Ibnu ‘Arabi terjadinya tajalli atau pengejawantahan Tuhan melalui
kosmos disebabkan oleh kehendak-Nya.
Dalam
sistem Ibnu ‘Arabi, wujud pada hakikatnya adalah satu, yakni wujud mutlak
(Allah) dan wujud mutlak ini bertajalli dalam tiga martabat. Dalam tiga
martabaat inilah Ibnu ‘Arabi sedikit meniru gaya Plotinus yaitu menyusun tiga
hipotesis secara hirarkis. Tiga martabat tersebut adalah :
1.
Martabat Aĥadiyyah atau Dzatiyyah,
yakni bahwa wujud Allah merupakan Dzat yang mutlak lagi mujarrad, atau
tidak terbayangkan. Merupakan The One dalam filsafat Neoplatonisme.
2.
Martabat Waĥidiyyah, disebut juga
martabat tajalli dzat atau fayd al aqdas (limpahan paling kudus). Dzat
yang mujarrad bertajalli melalui sifat dan asma. Dengan tajalli
ini Dzat tersebut menjadi pengikat sifat-sifat dan nama-nama yang maha
sempurna (asma’ul husna). Tetapi sifat dan nama tersebut berada
dalam satu sisi yang tidak berlainan atau identik dengan Dzat Allah. Inilah a’yan
tsabitah atau mafātiĥ al ghaib.
3.
Martabat tajalli Syuhudi. Disebut juga Fayd
muqaddas (limpahan kudus/ kedua) atau kenyataan kedua. Allah bertajalli melalui
asma dan sifat-Nya dalam keadaan kongkrit. Dengan perkataan lain melalui
firman-Nya, maka a’yan tshabitah yang dulunya merupakan wujud potensial
dalam Dzat ilahi, kini menjadi kenyataan aktual dalam berbagi citra alam
empiris. Alam empiris ini merupakan wadah atau mazhar tajalliillahi
dalam berbagai wujud atau bentuk yang tiada akhir.[28]
Ibnu Arabi memandang bahwa hakikat
wahdatul wujud merupakan sebuah perkara yang sangat agung dan "thuri warai
thur akal"[29] yang
membuat orang-orang berakal takjub dan mereka membutuhkan (media) pengenalan
yang lebih tinggi untuk memahami hal ini. Ia meyakini bahwa akal tidak dapat
diandalkan untuk menyerap hakikat wahdatul wujud. Lantaran Allah Swt pada
tingkatan penampakan (zhuhur) adalah identik dengan segala sesuatu. Namun Dia
tidak identik dengan segala sesuatu pada tataran esensi (zat). Perkara agung
ini bukan sekedar sepintas kontradiksi, melainkan benar-benar kontradiksi;
lantaran apabila kontrakdiksi hanya tampak secara lahir maka setelah
kontradiksi ini dapat diatasi maka ia tidak lagi agung dan tidak lagi membuat
orang-orang takjub.
Ibnu Arabi mengatakan, "Mengungkapkan hal ini benar-benar pelik. Lantaran kata-kata tidak mampu mengekspresikannya. Dan karena perubahan dan kontrakdiksi pada hukum-hukumnya maka benak tidak dapat merekamnya. Masalah ini seperti pada firman Allah Swt yang menyatakan: "Wama ramaita idz ramaita." (Kalian tidak melempar (pengingkaran) tatkala kalian melempar (penetapan)."[30]
Ibnu Arabi mengatakan, "Mengungkapkan hal ini benar-benar pelik. Lantaran kata-kata tidak mampu mengekspresikannya. Dan karena perubahan dan kontrakdiksi pada hukum-hukumnya maka benak tidak dapat merekamnya. Masalah ini seperti pada firman Allah Swt yang menyatakan: "Wama ramaita idz ramaita." (Kalian tidak melempar (pengingkaran) tatkala kalian melempar (penetapan)."[30]
Apa yang telah diuraikan di atas
adalah beberapa penjelasan dan ungkapan Ibnu Arabi terkait pembahasan wahdatul
wujud yang menjadi fokus utama kajian irfan teoritis.
BAB
III
PENUTUP
A.
Simpulan
Ibnu ‘Arabi adalah tokoh pemikir yang
mengangkat problem metafisika dengan menggunakan kerangka sufistik,
memandangnya melalui dzauq dan menguraikannya dengan akal murni,
sehingga apa yang diungkapkannya bersifat hakikat. Baginya hakikat adalah wujūd
dan wujūd adalah satu. Kalaupun nampak keanekaragaman, itu hanyalah
akibat dari keterbatasan indera dan rasio manusia dalam menangkap hakikat yang
satu. Disamping banyak yang mengecamnya banyak pula
para penulis tidak keberatan untuk mengatakan bahwa rumusan pemikiran dari
Kesatuan Wujud mengandung kedalaman, kejernihan dan kehalusan yang tidak
tertandingi. Prinsip ini bukan sekedar apresiasi dari ide intelektual seorang
tokoh genius, melainkan usaha pencarian makna hidup yang harus diungkapkan dan
diaktualisasikan. Waĥdatul wujūd tidak dapat disejajarkan dengan
kepercayaan kepada Yang Esa dalam konteks agama Ibrahim tertentu. Prinsip ini
bersifat absolut di luar pertentangan, meliputi semua kepercayaan dan doktrin.
Prinsip tersebut muncul dalam segala sesuatu namun tidak terkandung di dalam
segala sesuatu.
B.
Kritik dan Saran
Penulis
mengetahui dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan dan ketidak
sempurnaan,untuk itu penulis memohon kepada pembaca memberikan kritik dan saran
yang membangun, agar dalam penulisan selanjutnya bisa lebih baik lagi.
DAFTAR PUSTAKA
‘Arabi, Ibnu al. Futtuhat al Makiyyah. ed : Usman Yahya.
Kairo, 1979.
Abdurrahman Badawi, Ibnu ‘Arabi Hayatuhu wa Mazdhabuhu (Mesir,
Maktabah al-Anjalu al-Mhisriyyah, 1965
Affifi, A.E. Filsafat Mistis Ibnu ‘Arabi. terj. Sjahrir Mawi
dan Nandi Rahman. Jakarta : Gaya Media Pratama, 1995.
Austin, R.W.J. Sufi-sufi Andalusia. terj. M.S. Nasrullah.
Bandung : Mizan : 1994.
Daudy, Ahmad. Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syekh Nuruddin Ar
Raniri. Jakarta : Rajawali Perss, 1983.
Hirtenstein, Stephen. Dari Keragaman ke Kesatuan Wujud, Ajaran
dan Kehidupan Spiritual Syaik al Akbar Ibn ‘Arabi. terj. Tri Wibowo B.S.
Jakarta : Murai Kencana, 1999.
Kautsar Azhari Noer, Ibn Al’Arabi,
Waĥdatul wujūd dalam Perdebatan (Jakarta : Paramadina,1995 )
Mahmud Yunus, kamus arab indo (Jakarta: Hidakarya agung,
1990),
Nasution, Harun. Filsafat dan Mistisisme dalam Islam.
Jakarta : Bulan Bintang, 1995
smani, Rofi’. Tokoh-tokoh Muslim Pengukir Zaman. Bandung :
Penerbit Pustaka, 1998.
Supandi
Djoko Damono, (Pustaka Firdaus, 1975),
[1]
Stephen
Hirtenstein, Dari Keragaman ke Kesatuan Wujud, Ajaran dan Kehidupan
Spiritual Syaikh Al Akbar Ibnu ‘Arabi, terj. Tri Wibowo (Jakarta : Murai
Kencana 2001) h. 9.
[2] Abdurrahman
Badawi, Ibnu ‘Arabi Hayatuhu wa Mazdhabuhu (Mesir, Maktabah al-Anjalu
al-Mhisriyyah, 1965), h. 5.
[3] Ibid. h. 7.
[4] Hal ini sangat mungkin baginya karena Muhyiddin
berasal dari keluarga ningrat dan kaya. Pada usia delapan tahun, ia dan
keluarganya pindah dari Murcia ke Sevilla, ibukota Andalusia saat itu. Di
Sevilla, ayahnya bekerja pada Sultan Abu Ya’qub (Addas, 2004) h. 50.
[5] Stephen
Hirtenstein, Dari Keragaman ke Kesatuan Wujud,
h. 67-8.
[7] Ibid, h. 23.
[8]
A. Rofi’
Usmani, Tokoh-tokoh Muslim Pengukir Zaman (Bandung : Penerbit Pustaka,
1998),h. 30
[9] Kautsar Azhari
Noer, Ibn Al’Arabi, Waĥdatul wujūd dalam Perdebatan (Jakarta :
Paramadina,1995 ) h. 17.
[10] Stephen
Hirtenstein, Dari Keragaman ke Kesatuan Wujud, h.
67.
[12] Stephen
Hirtenstein, Ibid., h. 52. Dikutip dari G. Elmore, On the Road.
Seperti diceritakan Ibnu ‘Arabi kepada Ibnu al Sha’ar (1197-1256).
[13] A. Rofi’
Usmani, Tokoh-tokoh Muslim Pengukir Zaman (Bandung : Penerbit Pustaka,
1998) h. 30.
[14] Karya
Ibnu’Arabi mengenai kehidupan dan ajaran para sufi sezamannya adalah Ruh al
Quds dan Al Durrah al Fakhirah. Nama Madyan disebut berkali-kali
dalam Ruh al Quds.
[15] Lihat RWJ
Austin, Sufi-sufi Andalusia. Diterjemahkan dari Ruh al Quds dan Al
Durrah al Fakhirah, terj. MS. Nasrulloh (Bandung : Mizan, 1994) hlm. 148
–149.
[16] A. Rofi’Usmani,
Tokoh-tokoh Muslim Pengukir Zaman (Bandung : Penerbit Pustaka, 1998) h.
30.
[17]
A.E. Affifi, Filsafat Mistis Ibnu ‘Arabi, terj. Sjahrir Mawi dan Nandi
Rahman (Jakarta : GMP, 1995) h. 14.
[18]
Mahmud Yunus, kamus
arab indo (Jakarta: Hidakarya agung, 1990), h. 492 dan 494.
[19] Harun
Nasution, Filsafat dan Mistisisme
dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet III, h. 92.
[20]
William C. Chittick, Dunia Imajinal, h. 32.
[21]
A.E. Affifi, Filsafat Mistis Ibnu ‘Arabi, terj. Sjahrir
Mawi dan Nandi Rahman (Jakarta: GMP, 1995) h.
93
[22]
Ibid, h.
93
[23] Selain
menggunakan sinonim zuhur, tanazzul dan fath untuk tajjali,
Ibnu ‘Arabi juga menggunakan terminologi Plotinus emanasi (fayd) dengan
maksud berbeda. Lihat Kautsar Azhari Noer, Ibn al ‘Arabi, Waĥdatul
Wujūd dalam Perdebatan (Jakarta : Paramadina, 1995) hlm. 57.
[24] A.E. Affifi, Filsafat Mistis Ibnu ‘Arabi, terj. Sjahrir
Mawi dan Nandi Rahman (Jakarta: GMP, 1995) h.
91.
[26] Enneads I,
8, 14 dikutip oleh Ian Richard Netton, h. 41.
[27] Enneads II,
2, 2 dikutip oleh Ian Richard Netton, ibid.
[28] Ahmad Daudy, Allah
dan Manusia dalam Konsepsi Syekh Nurudding Ar Rini(Jakarta : Rajawali
Perss, 1983) h. 203. Menurut Kautsar, martabat ke 2 dan ke 3 disebut dua tipe
utama emanasi, yaitu emanasi paling suci dan emanasi suci. Lihat Kautsar, hlm. 62.
[29]Ibn Arabi, Al-Futuhat
al-Makkiyah, jil. 2, h. 484.
[30] Ibn Arabi, Al-Futuhat
al-Makkiyah, jil. 1, h. 289.
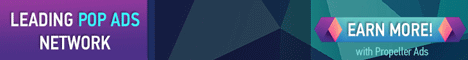

Tidak ada komentar:
Posting Komentar